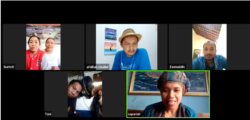Sejumlah mantan Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang pernah bekerja di kapal asing baru-baru ini mengungkap perlakuan tidak manusiawi selama bekerja di kapal penangkap ikan luar negeri.
Fredi asal Tegal, mengungkapkan durasi waktu kerja yang panjang tanpa istirahat yang cukup.
“Tidak ada istirahat sama sekali selama 30 jam kita berdiri. Makannya juga, setiap enam jam, makan tidak boleh lebih dari 15 menit, harus cepat. Untuk pola makanannya juga, namanya di tengah laut, banyak bahan makanan itu yang sudah kadaluarsa, tidak layak lagi untuk dimakan,” kata Fredi dalam diskusi virtual bertema “Di Balik 'Seafood' yang Kita Makan” (22/5) oleh Greenpeace Indonesia.
Karena sering mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa, ia dan rekan-rekanya mudah jatuh sakit. Sayangnya, menurut Fredi, obat-obatan yang tersedia di kapal juga sudah kadaluarsa.
Tony, asal Brebes, Jawa Tengah mengatakan saat hendak bekerja sebagai ABK dia harus menyetor uang sembilan juta rupiah kepada perusahaan penyalur tenaga kerja untuk biaya pemberangkatan ke Italia. Kontrak kerja baru diberikan dan ditandatangani menjelang keberangkatan ke Italia, sehingga tidak sempat membaca sebaik-baiknya isi kontrak yang disebutkan sangat tidak adil itu.
“Gaji saya ini sudah dua bulan tidak keluar. Saya sudah hubungi agen, katanya mau diurus, mau dikirim, padahal yang bertanggung jawab di sini bos Libya. Di sini tertulis, kalau kita sudah pulang ke Indonesia, adapun kekurangan atau tidak dibayar, agen tidak bertanggung jawab. Kan lucu. Perjanjian seperti itu menurut saya sepihak,” jelas Toni yang mengaku sedang berada di Libya.
Toni mengatakan seharusnya ada aturan yang mewajibkan perusahaan penangkapan ikan di luar negeri untuk menyediakan sarana komunikasi sehingga memudahkan kontak dengan keluarga di tanah air.
Afdillah, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, menyebutkan penangkapan ikan yang tidak mengindahkan prinsip kelestarian, menyebabkan berkurangnya stok ikan laut global, sehingga kapal-kapal penangkap ikan berlayar lebih lama di lautan, dan bahkan hingga berbulan-bulan. Untuk menekan kebutuhan biaya operasional mereka kemudian merekrut tenaga kerja murah di negara-negara kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Filipina.
“Untuk mencari tenaga kerja yang bisa dibayar murah itu mereka melirik negara-negara Asia Tenggara dan itu ada bukti Indonesia dan Filipina yang paling banyak, dan juga negara-negara yang regulasinya itu longgar dimana regulasi yang bisa dimainkan dan pejabat-pejabatnya korup serta pengawasannya tidak ketat dan itu cocok banget untuk Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi ladang mereka mencari ABK-ABK yang bisa direkrut, dipekerjakan dengan gaji murah dan diperlakukan dengan semena-mena,” papar Afdillah.
Dia menegaskan untuk mencegah praktek perbudakan di atas kapal penangkap ikan asing itu, Indonesia perlu segera meratifikasi konvensi ILO 188. Upaya diplomasi juga harus dilakukan agar negara-negara pengguna tenaga kerja Indonesia, seperti China dan Taiwan, melakukan upaya serupa.
“Kita mendorong pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi terhadap konvensi ILO 188 tapi tidak cukup sampai disitu. Indonesia juga harus segera mendesak, mengadvokasi negara-negara di mana teman-teman, saudara-saudara kita, mungkin China dan Taiwan, kedua negara belum meratifikasi itu,” kata Afdillah berharap.
Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan menggolongkan kegiatan penangkapan ikan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya sehingga memerlukan kondisi kerja yang layak. Kapal-kapal itu harus bisa menyediakan layanan kesehatan, akomodasi, makan dan keselamatan yang memadai, dan bahkan jaminan sosial. [yl/ab]